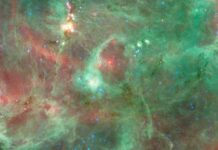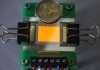KTT iklim COP30 yang baru saja selesai di Belém, Brasil, merupakan salah satu perundingan global yang paling penuh konflik dalam tiga dekade terakhir. Pembicaraan tersebut berakhir pada hari Sabtu tanpa komitmen konkrit untuk menghapuskan bahan bakar fosil, sehingga menyoroti kegagalan dalam konsensus internasional. Meskipun beberapa negara, khususnya produsen bahan bakar fosil, melihat hasil ini sebagai sebuah kemenangan, banyak negara lain yang merasa frustrasi karena kurangnya ambisi.
Hambatan Inti: Ketahanan Bahan Bakar Fosil
Permasalahan utamanya adalah penolakan beberapa negara utama untuk menyetujui peta jalan yang menjauhi batu bara, minyak, dan gas. Brasil, di bawah Presiden Lula da Silva, pada awalnya mendorong komitmen tersebut, bahkan mendapatkan dukungan awal dari negara-negara seperti Inggris. Namun, presiden COP André Corrêa do Lago lebih mengutamakan konsensus dibandingkan tindakan tegas, sehingga pada akhirnya mengesampingkan peta jalan bahan bakar fosil.
Negosiasi semakin memburuk ketika negara-negara Arab dan produsen besar seperti Arab Saudi dengan tegas menolak untuk terlibat dalam diskusi mengenai penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap, dimana salah satu delegasi dilaporkan mengatakan kepada perwakilan UE, “Kami membuat kebijakan energi di ibu kota kami, bukan di ibu kota Anda.” Kebuntuan ini menyebabkan Brasil mengusulkan peta jalan yang tidak mengikat mengenai deforestasi dan bahan bakar fosil di luar kerangka kerja formal COP—sebuah langkah yang tidak memiliki penegakan hukum.
Posisi UE yang Melemah
Uni Eropa tiba di COP30 untuk mengadvokasi peta jalan bahan bakar fosil, namun mereka terpojok pada pendanaan iklim. Perjanjian pendanaan adaptasi iklim “tiga kali lipat” dimasukkan dalam rancangan akhir tanpa adanya keberatan yang jelas dari UE, sehingga membuat mereka tidak mempunyai pengaruh yang besar untuk mendorong tindakan yang lebih kuat terhadap bahan bakar fosil. Para ahli seperti Li Shuo dari Asia Society mencatat adanya “pergeseran kekuasaan” yang menguntungkan negara-negara di blok BASIC dan BRIC, sehingga mengurangi pengaruh UE. Upaya UE untuk mendapatkan konsesi bahan bakar fosil pada akhirnya gagal, sehingga memaksa mereka untuk menerima perjanjian tersebut dengan keuntungan yang minimal.
Masa Depan Proses COP
KTT ini memunculkan kembali pertanyaan mengenai relevansi proses COP itu sendiri. Kritikus menunjuk pada ketidakpraktisan logistik dari pertemuan puncak global tahunan dan lambatnya kemajuan. Aktivis Harjeet Singh berpendapat bahwa model COP memerlukan “retrofit” dan harus dilengkapi dengan inisiatif eksternal. Seiring dengan perkembangan pesat lanskap energi global, kerangka kerja COP yang berdasarkan konsensus tampaknya sudah ketinggalan zaman.
Sengketa Dagang Memasuki Arena Perubahan Iklim
Untuk pertama kalinya, perdagangan global muncul sebagai isu sentral dalam pertemuan puncak tersebut. Rencana pajak karbon perbatasan Uni Eropa terhadap barang-barang beremisi tinggi memicu penolakan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, dan Arab Saudi, yang memandang tindakan tersebut tidak adil dan proteksionis. Meskipun UE berpendapat bahwa pajak tersebut dirancang untuk memberi insentif pada produksi yang lebih bersih, para kritikus berpendapat bahwa hal tersebut akan merugikan negara-negara berkembang. Perselisihan ini pada akhirnya ditunda hingga perundingan di masa depan, yang menyoroti semakin meningkatnya persinggungan antara kebijakan iklim dan perdagangan internasional.
Tiongkok dan AS: Strategi yang Berbeda
Dua negara penghasil emisi terbesar di dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, mendekati COP30 dengan strategi yang berbeda. AS, yang kemungkinan besar berada di bawah pemerintahan Trump, masih banyak yang tidak hadir, sehingga mendorong sekutu seperti Rusia untuk menghalangi kemajuan. Sebaliknya, Tiongkok tidak terlalu menonjolkan diri dalam politik dan diam-diam mendapatkan keuntungan ekonomi di sektor energi terbarukan. Seperti yang diamati oleh Li Shuo, “Tiongkok tidak menonjolkan diri dalam politik…dan mereka fokus menghasilkan uang di dunia nyata.” Dengan semakin kompetitifnya energi surya, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pemain dominan di pasar energi masa depan.
Sebagai kesimpulan, COP30 menggarisbawahi semakin besarnya kesenjangan antar negara dalam aksi iklim. KTT tersebut gagal menghasilkan komitmen yang berarti mengenai bahan bakar fosil, perselisihan perdagangan memperumit negosiasi, dan kelangsungan proses COP dalam jangka panjang kini dipertanyakan. Lintasan iklim dunia masih belum menentu karena realitas geopolitik semakin menutupi pentingnya tindakan kolektif.